Teman-teman pengunjung sivalintar.com yang budiman, perkenankan aku melanjutkan kisah
pengalamanku, kisah biasa dari orang biasa. Mudah-mudahan kisahku ini tidak sekedar
ungakapn pengalaman batin semata yang hanya enak untuk dibaca tetapi tidak berarti
apa-apa bagiku maupun orang lain. Aku berharap kisah ini bisa memberi inspirasi sekecil
apapun itu, bagi siapa saja yang membacanya
Merenung Sejenak
Raut mukanya murung, tatapan matanya kosong,
air matanya meleleh membasahi pipinya yang agak kotor terkena debu. Bibirnya bergetar
menggumamkan sesuatu, lirih hampir tak terdengar, "Ya Tuhan, betapa berat cobaan yang
Engkau berikan ini."
|
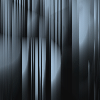 Sebelum melanjutkan kisah pengalamanku ini, aku ingin mengajak anda merenung sejenak.
Mengajak (imajinasi) anda mengunjungi sebuah desa yang sunyi dan tenang. Bayangkan,
suatu sore anda berdiri dipinggir pesawahan dengan hijaunya hamparan padi. Daun-daun padi
itu bergoyang searah hembusan angin yang terasa sejuk. Lihatlah ke seberang sawah sebelah
sana, lurus di hadapan anda, beberapa ekor domba yang tampak montok dan sehat sedang
merumput dengan lahapnya di pematang-pematang pinggir sawah.
Sebelum melanjutkan kisah pengalamanku ini, aku ingin mengajak anda merenung sejenak.
Mengajak (imajinasi) anda mengunjungi sebuah desa yang sunyi dan tenang. Bayangkan,
suatu sore anda berdiri dipinggir pesawahan dengan hijaunya hamparan padi. Daun-daun padi
itu bergoyang searah hembusan angin yang terasa sejuk. Lihatlah ke seberang sawah sebelah
sana, lurus di hadapan anda, beberapa ekor domba yang tampak montok dan sehat sedang
merumput dengan lahapnya di pematang-pematang pinggir sawah.
Di bawah pohon rambutan yang rindang, duduk seorang remaja tanggung memperhatikan
domba-domba gembalaanya, tangannya memegang sebuah buku. Lihatlah lebih dekat lagi,
ternyata si gembala domba ini tidak sedang mengawasi domba-dombanya, dan buku yang
dipegangnya sama sekali tidak dibacanya. Raut mukanya murung, tatapan matanya kosong,
air matanya meleleh membasahi pipinya yang agak kotor terkena debu. Bibirnya bergetar
menggumamkan sesuatu, lirih hampir tak terdengar, "Ya Tuhan, betapa berat cobaan yang
Engkau berikan ini." Suara alunan musik dangdut yang mendayu-dayu dari radio transistor
kecil yang selalu dibawanya mengembala, sama sekali tidak mampu menghiburnya. Tak ada
yang mampu menghiburnya, meredakan gejolak batinnya yang makin tak terkendali.
Seorang anak desa yang sepulang sekolah pekerjaanya hanya menggembala domba dan menyabit
rumput-yang bahkan belum kenal istilah psikologi, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan
pahit, menderita gangguan bipolar kronis. Penyakit jiwa yang sama sekali tidak
dipahaminya, tidak diketahui apa penyebabnya, tidak tahu cara mengatasinya, bahkan tidak
tahu harus berbuat apa. Kian hari penyakit itu kian ganas mengoyak-ngoyak pikiran dan
perasaannya. Saat gejolak batinnya makin tak terkendali, yang mampu dilakukannya hanya
menangis. Ia tak berani menceritakan derita jiwanya kepada orang lain, termasuk kepada
teman dan sahabat dekatnya. Bahkan kepada orang tuanya sendiri pun ia tak berani bercerita.
Anda ingin tahu lanjutan kisah si gembala domba penderita manic depressive ini?
Silakan buka halaman berikutnya.
Obrolan di Gubug Sawah
Sore itu cuaca mendung, sepertinya tidak lama lagi akan turun hujan lebat. Hamparan padi
yang mulai menguning tampak bergoyang-goyang ditiup angin. Musim tanam sekarang sepertinya
padi tidak sebagus seperti musim tanam yang lalu.
Walaupun setahun lebih aku tidak pernah melihat sawah orang tuaku yang tidak seberapa luas,
tapi suasananya tampak tidak banyak berubah, bahkan hampir sama seperti saat 14 tahun yang
lalu, saat aku sedang menderita depresi berat.
Gubuk tempatku berteduh sekarang masih tetap ditempatnya seperti dulu. Bedannya kalau
dulu bertiang bambu dan beratap ilalang, sekarang bertiang kayu dan beratap genting.
Namun tampak sudah tua, setua ayahku yang setiap hari berteduh, melepas lelah sehabis
bekerja di sawah. Dulu aku sering tidur dengan ayah di gubuk ini, menunggui padi yang
baru dipanen. Selain menanam padi, di pematang sawah ayah juga menanam bermacam-macam
jenis sayuran, sekedar untuk dimasak sendiri. Ayah juga memelihara beberapa ekor itik
di kolam kecil di bagian atas petakan sawah yang tidak ditanami padi.
Sore itu aku sengaja menemui ayah di sawah, sekedar untuk ngobrol. Hari itu aku ambil
cuti jadi aku bisa leluasa ngobrol tentang segala hal dengan ayah.
"Kalau melihat suasana di pesawahan ini, ada rasa getir," kataku seraya melihat sekeliling
sejauh batas pandangan mata. "Aku suka ingat masa lalu, saat aku menderita gangguan jiwa
dulu, pak!"
Ayah hanya diam mendengar gumamanku, namun aku yakin ayahku ingat keadaanku 14 tahun yang
lalu.
"Setelah aku banyak membaca buku, surat kabar dan majalah, sekarang aku tahu nama
penyakit itu," kataku melanjutkan tanpa menunggu tanggapan ayah. "Penyebabnya sampai
sekarang memang tidak jelas, tapi salah satu kemungkinan penyebabnya adalah faktor
keturunan."
"Memang, bapak juga dulu pernah mengalami walaupun tidak separah kamu," kata ayah,
"Mendengar sedikit saja omongan orang yang tidak enak, ayah selalu memikirkan."
"Dari buku-buku, majalah dan surat kabar yang aku kumpulkan dan aku pelajari, sekarang
aku sudah tahu penyakit apa yang aku derita itu. Namanya gangguan Bipolar, disebut juga
manic depressive," kataku menjelaskan.
"Syukurlah sekarang kamu sudah sembuh," kata ayah singkat. Lalu kami berdua sama- sama
diam.
Obrolan kami berlanjut kepada pembicaraan mengenai pekerjaanku dan seputar masalah-masalah
keluarga. mengobrol seperti inilah yang sering kami lakukan saat-saat aku sakit dulu.
Kami sering melakukannya berjam-jam bahkan sampai larut malam. Aku merasakan dialog-dialog
seperti ini bisa mengurangi beban pikiranku. Dalam melalui saat-saat getir seperti itu
ayahku telah menjadi penasihat, konselor, motivator, sekaligus sahabat dan teman curhatku.
Saat itu mungkin hanya ayahku yang bisa memahami keadaanku, memahami gejolak jiwaku,
walaupun tidak sepenuhnya. Aku bersyukur punya seorang ayah yang bijaksana. Kesabaran
dan perhatiannya saat aku menghadapi masa-masa sulit luar biasa. Tanpa perhatian, nasihat
dan bimbingannya yang penuh kasih sayang aku tidak tahu akan seperti apa kondisi jiwaku
saat itu. Terima kasih ayah!
Hari sudah semakin sore, mendung tampak semakin tebal menggulung, sepertinya hujan akan
segera turun. Aku pamit pulang pada ayah. Aku melewati jalan setapak yang dulu sering
aku lewati pergi-pulang ke sawah. Ingatanku kembali ke masa 14 tahun yang lalu,
saat-saat yang penuh kesedihan dan kegetiran. Aku ingat, saat itu aku baru selesai
melaksanakan ujian akhir, dulu disebut Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS).
Aku tinggal menunggu pengumuman kelulusan dan tidak lama lagi aku akan memasuki
lingkungan sekolah baru, aku akan melanjutkan ke SMA.
Menjelang Masuk SMA
Setelah kelulusan sampai menjelang masuk SMA, kondisi kejiwaanku bukannya membaik, tapi
sebaliknya semakin memburuk. Setelah pengumuman kelulusan, menjelang acara perpisahan dan
kenaikan kelas bagi siswa kelas 2 dan kelas 1, untuk mengisi kekosongan waktu (saat itu
menjelang bulan Ramadhan) sekolah menyelenggarakan kegiatan keagamaan "Pesantren Kilat"
biasa disingkat "Sanlat". Pesertanya gabungan siswa SMP dan SMA Islam yang masih dikelola
oleh yayasan yang sama. Sanlat dimulai sejak hari pertama bulan Ramadhan selama seminggu.
Pesertanya berjumlah sekitar 30 orang, putra 20 orang dan putri 10 orang. Pengajar dan
penceramahnya guru-guru SMP dan SMA tersebut. Ada juga penceramah dari sekolah lain.
Selama seminggu kami digembleng ilmu-ilmu keislaman. Kegiatan belajarnya meliputi diskusi,
kajian Al-Qur`an dan Hadits serta materi-materi keislaman lainnya. Metode dan materi
pelajarannya menarik sebenarnya, kebanyakan berupa ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan.
Namun, justru di sinilah masalahnya bagiku. Aku melihat dan menilai peserta lain—terutama
siswa SMA—begitu aktif berdebat dalam forum-forum diskusi, beradu argumentasi dengan
peserta lain dan stap pengajar. Mereka juga tampak akrab dengan para pengajar. Sedangkan
aku, seperti biasa merasa rendah diri di hadapan mereka semua, karena aku merasa tidak
pandai berdiskusi dan berdebat apalagi baradu argumentasi. Di ruang belajar aku lebih
banyak berdiam diri. Aku juga merasa kurang mampu bergaul dengan staf pengajar maupun
dengan peserta lain. Semakin aku pikirkan semakin aku merasa minder. Setiap hari yang
aku pikirkan bukannya materi-materi pelajaran agama, aku malah lebih memikirkan
ketidakmampuanku berkomunikasi dan berdebat di forum diskusi. Jadilah, hari-hari di
Sanlat aku jalani dengan perasaan minder dan tertekan.
Kepercayaan diriku benar-benar anjlok. Betapa tidak, aku yang tadinya cukup percaya
diri dengan prestasi belajarku di sekolah, melihat kemampuan peserta-peserta lain,
terutama siswa-siswa SMA di forum Sanlat, aku merasa tidak memiliki kelebihan apa-apa.
Aku merasa menjadi peserta Sanlat paling pasif. Aku benar-benar merasa menjadi peserta
yang paling bodoh.
Selesai mengikuti Sanlat selama sepekan penuh, aku memperoleh wawasan dan
pemahaman-pemahaman tentang ilmu-ilmu keagamaan. Namun dibalik itu aku mendapati diriku
yang merasa tersisihkan dan kurang percaya diri.
Halaman :
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16
|

